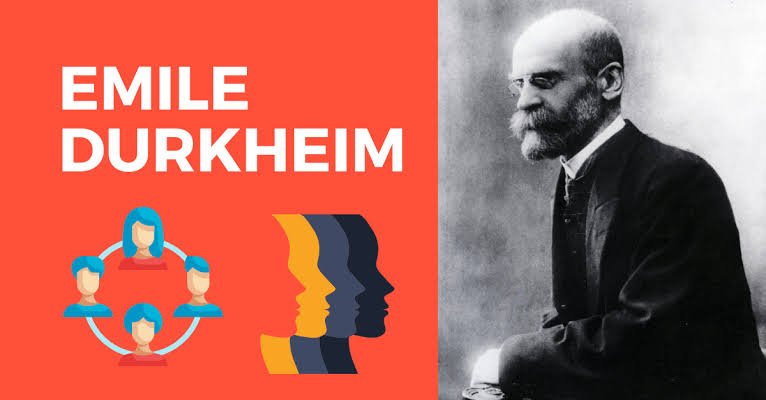AswajaNews – Logika materialisme dapat dikatakan menjadi bagian dari dialektika yang mengilhami adanya Soviet, terjadi karena dialektika antara Engel dan Stalin. Dalam persoalan ini, Emil Durkheim bisa dikategorikan sebagai penerus yang lihai dalam melihat dialektika tersebut.
Sosiologi Durkheim tentu berbeda dengan sosiologi ala Marx Weber yang lebih mengarah ke fungsionalis_ yang mengasumsikan bahwa dunia sosial adalah dunia yang dibentuk oleh dunia individu. Atau sedikit berbeda dengan sosiologi ala Ibn Khaldun, misalnya tentang siklus parallel (mengulang) yang mengakui keterbatasan terhadap sesuatu hal_ yang lebih menekankan tesis dan anti-tesis. Bahwa teori sosial dapat muncul atau bangkit dari individu atau atas common sense, hingga akhirnya menentukan mana kesadaran yang akhirnya dipilih.
Namun, dalam hal ini, sosiologi Ibn Khaldun mungkin “lebih cocok” untuk disandingkan dengan gaya sosiologinya Durkheim (meski terkesan agak sedikit memaksa, tapi paling tidak keduanya sama-sama berbicara mengenai siklus yang saling berkaitan)
Ini seolah sama dengan hakikat ilmu pengetahuan yang lahir tidak secara mandiri dan punya ikatan-ikatan dengan dunia di luar jangkauannya, hingga kemudian memunculkan pemikiran yang sedemikian.
Mereka pun mempunyai batasan dan jangkauan masing-masing, misalnya geografi, kondisi sosio-budaya masyarakat hingga ekonomi-politik. Kalau dalam filsafat kita mengenal istilah bahwa langkah manusia untuk mengetahui adalah proses yang cukup panjang dan rumit.
Misalnya, filsuf di Jerman yang cenderung idealism akan kesulitan untuk beraliran rasionalisme. Filsuf Prancis yang rasionalisme akan kesulitan untuk berfikir secara empiris. Filsuf Inggris yang cenderung empiris akan kesulitan untuk pragmatis seperti Filsuf Amerika. Dan seterusnya.
Durkheim maupun Ibn Khaldun, dan juga pemikir sosiologi lainnya juga tidak luput dari “bias-bias” ini. Mereka mempunyai pandangan berbeda mengenai relasi sosiologi dan agama karena proses yang mereka lakukan juga berbeda.
Dalam hal ini, penulis tidak hendak berpanjang ria mengurai tentang “konfrontasi” antara tokoh-tokoh tersebut. Biarkan ia menjadi pekerjaan rumah dari sejarah kehidupan manusia. Biarkan ia tumbuh dengan mesra bersama kehidupan yang terus berubah-ubah tak menentu dan kehidupan yang tumbuh dengan cepat ini.
Tidak juga, pemikiran Durkheim yang “mungkin” begitu megah dan menyebabkan efek samping kepala pusing tersebut hendak penulis ringkas menjadi catatan yang pendek ini. Penulis hanya berupaya memahamai (sesuai kemampuan yang maksimal) tentang sosiologi Durkheim yang kemudian dapat digunakan, sekurang-kurangnya dalam upaya memahami kondisi masyarakat, terlebih masyarakat yang beragama.
Bicara tentang Durkheim, tentu tidak bisa dilepaskan dengan sosiologi strukturalis, namun yang menjadi khas atau keunikan dari sosiologinya adalah ketika kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial solidaritas mekanik dan kelompok yang didasarkan pada solidaritas organik. Solidartas mekanik merupakan ciri masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja, sedangkan organik adalah sebaliknya.
Untuk melacak keduanya dapat dilihat dan dipahami bahwa kesadaran kolektif/mekanik adalah kesadaran yang didorong atas sesuatu yang bersifat non-materil, misalnya agama dan norma-norma sosial lainnya. Sedangkan kesadaran organik adalah keasadaran yang memahami bahwa semua memiliki medan yang terpisah-pisah namun saling berelasi.
Makna terakhir inilah yang dinamakan siklus yang saling berkaitan. Ini yang kemudian menjadi titik pijak sosiologi dari Durkheim, bahwa dunia sosial lah yang pada akhirnya membentuk kesadaran individu. Dan tentu berbeda dengan Weber yang mengatakan bahwa dunia sosial adalah dunia yang dibentuk dari dunia individu.
Dalam rangka melihat bagaimana posisi agama dalam sosiologi Durkheim, penulis perlu mengutip pendapatnya, ”Agama hanya dipandang sebagai suatu khayal untuk mempertahankan atau melestarikan kelompoknya sendiri.” Apa yang menjadi statemen Durkheim tersebut tidak perlu kita disikapi dengan emosi yang menggebu-gebu apalagi sampai menaikkan urat saraf.
Agap saja sebagai sindiran yang memang perlu, mengingat kita membutuhkan hal semacam itu agar lebih dewasa lagi dalam beragama, baik pada wilayah pemaknaan maupun aplikatifnya. Karena bagaimanapun, ukhuwah yang ditafsirkan secara kolot dan salah malah akan membenarkan pendapat Durkheim tersebut. Kita harus menjadi manusia yang dinamis, dan dalam bahasa Durkheim dinamakan dengan kesadaran organik.
Sudah saatnya kita memperjuangkan persaudaraan yang sama-sama pasrah dan tunduk kepada-Nya, bukan persaudaraan sesama Islam saja, Kristen saja atau atas satu agama saja. Penulis meyakini setiap agama apapun pasti mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat baik kepada sesama, selain kepada Tuhannya. Sama-sama memperjuangkan haknya sebagai manusia.
Makna jihat adalah kerja memanusiakan manusia demi terwujudnya cinta di dunia. Penafsiran yang salah malah akan mengerdilkan kemanusiaan kita dan bagaimanapun kesucian agama itu dilihat dari manusia dalam menjalankannya bukan pakaian atau peralatan fisik yang digunakan.
Kita tidak boleh kehilangan cinta, kepada Tuhan, kepada sesama makhluk apalagi kepada diri sendiri. Pengakuan jujur tentang keterbatasan sebagai manusia dan juga sikap terbuka dalam usaha berakhlak mulia dalam kreatifitas disegala hal harus segera direalisasikan.
Kita juga harus memandang kebenaran bukan karena orang yang mengatakan, tetapi melihat kebenaran sebagai kebenaran. Ini adalah peringatan bahwa jangan lagi mudah menyalahkan, karena perjuangan orang-orang yang kita benci sekalipun bukan berarti untuk sesuatu yang kurang mulia.
Kebencian itu didasarkan ketidaktahuan, jadi jangan meletakan pengetahuan pada kepercayaan yang sempit. Perbedaanpun harus kita sikapi secara dewasa dengan tidak merasa paling benar, bahwa sikap yang hanya mengakui dan membenarkan satu pendapat saja adalah dekat dengan kekafiran dan pertentangan. Wallahu A’lam.***
Penulis: Dani